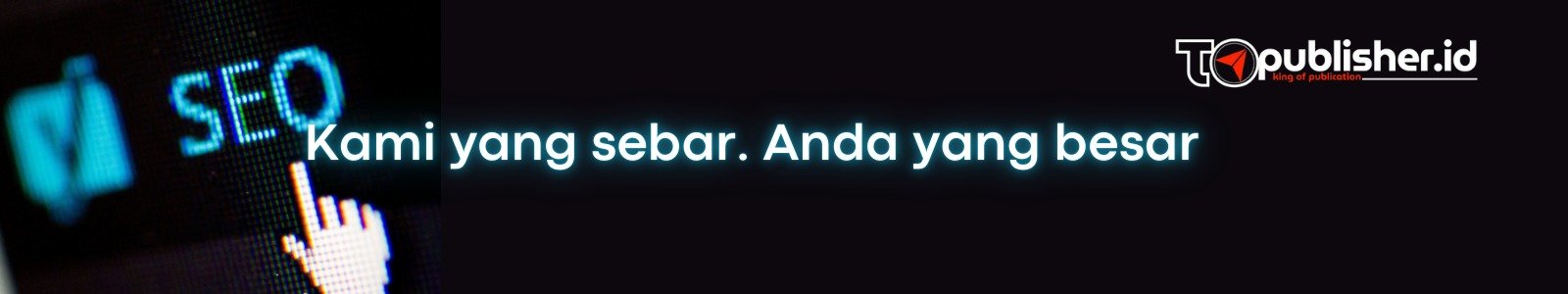Moneter.co.id – Dalam kurun
waktu tiga tahun sejak 2014 hingga 2017 atau semenjak pemerintahan Joko
Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), tercatat menambah utang sebesar Rp 1.258,67
triliun.
Berdasarkan
data yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), hingga September 2017 posisi utang
luar negeri pemerintah mencapai 172,37 miliar dollar, ditambah utang BI 175,91
miliar dollar.
Direktur
Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri
Hartati mengingatkan soal utang negara perlu menjadi perhatian, mengingat
defisit anggaran primer terus naik secara signifikan. Ini menandakan beban
bunga dan cicilan utang sudah cukup besar.
“Penerimaan pajak
kita turun, maka konsekuensinya untuk memenuhi bunga dan cicilan sebagian
diambil dari utang yang baru. Tentu saja ini mempengaruhi pada produktifitas
dari utang-utang yang kita tarik,” kata Enny.
Menurut Enny, beban semakin bertambah,
karena proyek-proyek infrastruktur baru yang sumber pembiayaanya berasal dari
utang tersebut tidak bisa menghasilkan uang atau arus kas baru lagi dalam
jangka pendek.
Selain itu, kata Enny, ternyata pembangunan
infrastruktur juga dianggap belum mampu menyerap tenaga kerja yang lebih
banyak, sehingga tidak berdampak pada kenaikan konsumsi masyarakat. “Padahal,
konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dia mengatakan, penambahan utang yang
dilakukan pemerintah tidak mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan
penerimaan pemerintah. Sehingga secara cash flow, secara tata kelola keuangan,
pemerintah tekor.
“Jadi
investasi terus, pengeluaran terus berlangsung, tapi pendapatanya justru
menurun. Ini yang disebut, salah satunya menjadi risiko fiskal yang
membahayakan kesinambungan fiskal dari pemerintah, ” katanya.
Meski begitu, lebih jauh Enny
menjelaskan jika proyek infrastruktur ditugaskan kepada BUMN, maka dampaknya tidak
memberi multiplier effect yang besar kepada pembangunan nasional secara
keseluruhan.Hal ini disebabkan karena BUMN hanya berpikir bagaimana mengerjakan
proyek itu hingga selesai dan tidak memikirkan efek jangka panjang.
“Saya pernah
dengar pernyataan, setelah pembangunan proyek selesai maka aset yang dihasilkan
dari proyek itu langsung dijual. Ibaratnya kalau biaya pembangunan Rp10 triliun
lalu dijual Rp30 triliun, negara untung Rp20 triliun. Itu pola pikir yang
salah, karena pembangunan infrastruktur itu tidak bisa disamakan dengan jual
beli seperti itu,” jelasnya.
Namun begitu, menurut Enny lebih baik
pemerintah memberi kesempatan kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek
infrastruktur strategis. Karena dengan begitu APBN tidak terbebani.
“Kalau swasta
kan memang orientasinya menghasilkan laba, penting agar swasta terlibat secara
dalam pembangunan. Jika swasta dilibatkan, maka dunia usaha juga akan lebih
bergairah, hal ini yang menjadi mesin penggerak konsumsi, yang akhirnya
menggerakan pertumbuhan ekonomi itu sendiri,” terangnya.
Sementara, Ekonom Universitas
Brawijaya Candra Fajri Ananda menambahkan, utang masih belum menunjukan dampak
yang signifikan. Meski pemerintah berdalih untuk pembangunan infrastruktur,
tetapi dampaknya sangat panjang.
“Dana desa
mungkin bisa, buat bangun irigasi, kemudian muncul aktivitas ekonomi baru
walaupun kecil-kecil. Tetapi yang gede-gede, seperti pelabuhan dan tol, itu
butuh waktu. Apalagi kalau yang baru, ini yang tidak dikalkulasi,” kata Candra.
Karenanya, perlu dievaluasi lagi
proyek paling strategis mana yang paling dinomorsatukan dan cepat menghasilkan
dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Candra melihat, semua pembangunan
infrastruktur tersebut sangat berlebihan.
“Itu karena
konsekuensi politik ya. Pak Jokowi sudah berjanji, kalau sudah ditulis RPJMN
itu punya konsekuensi hukum. DPR bisa mempertanyakan, kenapa ini?,” ujarnya.
Candra menambahkan, seyogyanya
pembangunan infrastruktur ditunjang oleh pembiayaan yang memadai. Artinya,
anggaran pembangunan infrastruktur harus ditinjau pula dari pos pendapatan
negara, misalnya dari pos penerimaan perpajakan. Namun, pemerintah tidak bisa
terlalu menggenjot sektor pajak, yang membuat pembiayaan anggaran
ujung-ujungnya harus diambil dari utang.
“Dari anggaran
penerimaan negara dari perpajakan di APBN-P sebesar Rp1.472,7 triliun, sekitar
sepertiga penerimaan pajak digunakan untuk membayar utang beserta bunganya.
Untuk itu diperlukan evaluasi infrastruktur mana yang perlu diselesaikan
terlebih dahulu. Saat ini pemerintah terkesan memaksa harus menyelesaikan
pembangunan pada jangka waktu dekat ini,” jelasnya.
Menurut Candra, bahwa sebenarnya
posisi utang Indonesia saat ini masih terkontrol. Hal ini terlihat dari rasio
utang terhadap PDB Indonesia yang berada di posisi 28,1%. Meski demikian, efek
dari pembangunan infrastruktur baru bisa dirasakan dalam jangka panjang,
sekitar lebih dari 10 tahun. Sementara, utang pemerintah Indonesia sebagian
besar jatuh tempo dalam 3-5 tahun.
Menurut data dari Kemenkeu, jika
dilihat dari posisi jatuh tempo, 39,7% dari total outstanding utang Indonesia
jatuh tempo dalam lima tahun. Sementara 25,2% utang Indonesia jatuh tempo dalam
tiga tahun dan 9,7% jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
“Untuk itu perlu dilakukan evaluasi
lagi infrastruktur mana yang memang diperlukan. Dari beberapa bukti empiris di
banyak negara memang infrastruktur itu mampu mendorong penyerapan kerja.
Misalnya pembangunan jalan tol, proyek-proyek yang kalau dikelola dia bisa
menghasilkan cost recovery,”
tegasnya.
“Kalau
seperti tol laut, itu kan mahal biayanya. Itu destinasinya dari point to point
terlalu jauh dari sini sampai Papua, padahal biasanya UKM butuhnya yang
kecil-kecil pendek-pendek,” pungkasnya.
(SAM)